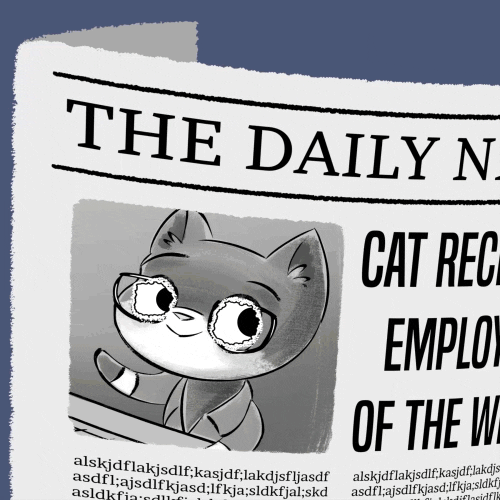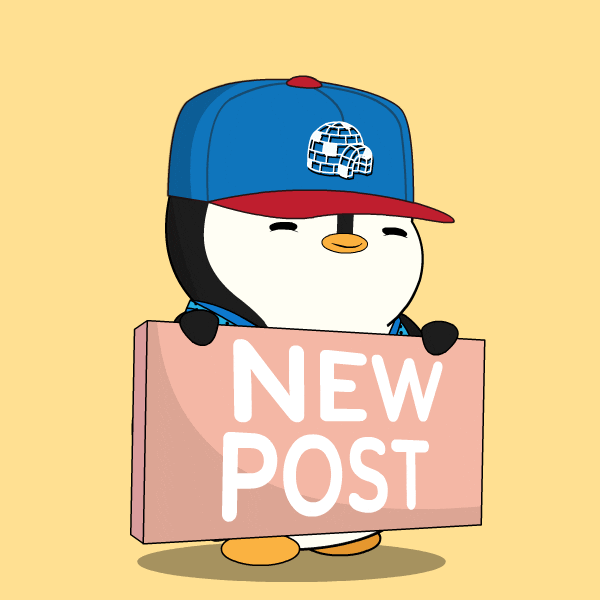Surabaya, LIRATV.ID – Di tengah gejolak politik pasca-Agustus 2025, Indonesia menghadapi badai sosial yang mengguncang fondasi demokrasi. Represi terhadap protes rakyat semakin nyata, dengan aktivis ditangkap dan demonstrasi dibubarkan, sementara kelas menengah runtuh ke titik terendah sejak era reformasi. Analisis mendalam dari pakar ilmu politik menyoroti penolakan negara untuk “bercermin” pada realitas pahit ini, yang berpotensi memicu krisis legitimasi nasional.
Dalam esai terbarunya, Airlangga Pribadi Kusman dosen Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga sekaligus Direktur Eksekutif Centre of Statecraft and Citizenship Studies (CSCS) FISIP Unair, mengungkap bagaimana ketimpangan struktural dan pemiskinan kelas menengah menjadi bom waktu sosial.
“Negara membanting cermin yang menunjukkan retakan fondasi sosial-ekonomi kita,” tegas Airlangga.
“Alih-alih dialog, elite memilih represi, mengabaikan aspirasi rakyat yang semakin terpinggirkan.” Ungkapnya lagi.
Runtuhnya Kelas Menengah, Dari Penyangga Demokrasi ke Korban Sistem
Kelas menengah, yang selama ini menjadi motor mobilitas sosial, konsumen utama ekonomi, dan pilar demokrasi partisipatif, kini ambruk. Data menunjukkan, antara 2019 hingga 2024, sekitar 9 juta orang terperosok dari kelas menengah ke kelas bawah. Ini bukan angka abstrak, melainkan kisah nyata degradasi hidup, manajer yang ter-PHK beralih jadi pengemudi ojek online (ojol), atau keluarga yang berhutang demi biaya kuliah di universitas negeri yang semakin mahal.
Fenomena ini, yang dikenal sebagai deprivasi relatif, menciptakan jurang antara ekspektasi hidup lebih baik dibangun dari pendidikan dan janji pembangunan dengan realitas stagnasi pendapatan, biaya hidup melonjak, dan privatisasi layanan dasar. Kekecewaan ini meluap menjadi gerakan sosial, dari aksi buruh dan mahasiswa hingga solidaritas ribuan pengemudi ojol.
Puncak tragedi terjadi pada 28 Agustus 2025, ketika pengemudi Affan Kurniawan tewas ditabrak saat demonstrasi di Jakarta. Insiden ini memicu gelombang protes nasional, bukan hanya untuk keadilan bagi Affan, tapi juga melawan kerapuhan posisi sosial kelas menengah yang terdegradasi.
Jumlah ojol melonjak drastis, dan data BPJS mencatat 2 juta pekerja, sementara perusahaan seperti Maxim memperkirakan hingga 7 juta mitra, dengan,7 juta di antaranya tanpa perlindungan sosial. Ojol, simbol fleksibilitas digital, kini jadi lambang kemunduran: mobilitas sosial berbalik dari atas ke bawah.
Represi sebagai Respons yang Salah: Ironi Demokrasi Indonesia
Alih-alih mendengar alarm ini, negara merespons dengan represi. Aktivis seperti Delpedro Marhaen (Direktur Eksekutif Lokataru Foundation), yang mendukung advokasi hukum pelajar, dan M. Fakhrurrozi alias Paul dari Social Movement Institute, ditahan tanpa alasan kuat.
“Mereka bukan kriminal, tapi pilar masyarakat sipil yang mengisi kekosongan kanal politik formal seperti partai dan parlemen yang lumpuh,” kata Airlangga.

Ironi ini menggemakan teori filsuf Jerman, Jürgen Habermas dalam bukunya Legitimation Crisis(1973), krisis legitimasi muncul saat “sistem” (negara, pasar, birokrasi) bertabrakan dengan “lifeworld” (kehidupan sehari-hari rakyat). Di Indonesia, klaim elite soal kemajuan ekonomi bertemu realitas biaya hidup tinggi, pendidikan mahal, dan lapangan kerja menyempit. Hasilnya? Runtuhnya kepercayaan publik, yang bisa memicu instabilitas seperti di Nepal (protes sejak September 2025) atau Amerika Latin.
Sejarah politik modern menunjukkan, kelas menengah yang hancur sering jadi sumber gejolak. Represi jangka pendek mungkin efektif, tapi justru menutup saluran aspirasi damai, menumpuk ketidakpuasan seperti gunung berapi siap meletus. Agenda 17+8 dari gerakan sosial paket solusi untuk reformasi demokrasi dianggap remeh, sementara elite sibuk dengan konsensus internal.
Panggilan untuk Aksi Waktunya Bercermin dan Bereformasi
Indonesia berada di persimpangan berbahaya. “Demokrasi bertahan hanya jika rakyat percaya suara mereka didengar, “Ketidakpercayaan adalah racun mematikan bagi negara,” ungkap Airlangga.
Untuk menjaga stabilitas, pemerintah harus:
– Mengakui runtuhnya kelas menengah dan krisis sosialnya.
– Membuka dialog dengan masyarakat sipil, bukan represi.
– Menjawab agenda rakyat seperti 17+8 secara konkret.
– Mereformasi kanal politik agar partai dan parlemen kembali relevan.
Tanpa langkah ini, negara berisiko kehilangan legitimasi total. “Rezim yang gagal bercermin akan dihancurkan oleh bayangannya sendiri,” tutup Airlangga, mengingatkan bahwa kedaulatanat adalah akar demokrasi.
Esai lengkap ini dirilis untuk mengajak diskusi nasional mendalam. Untuk wawancara atau informasi lebih lanjut, hubungi Centre of Statecraft and Citizenship Studies (CSCS) FISIP Universitas Airlangga di cscs.fisip@unair.ac.id.
Tentang Penulis:
Airlangga Pribadi Kusman adalah dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga dan Direktur Eksekutif CSCS, fokus pada statecraft, citizenship, dan dinamika politik kontemporer Indonesia. (Bar/Redsus)
 Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di
Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di